
Oleh: Choirul Anam*
blokBojonegoro.com - Kalau ada satu suara alam yang dulu paling mudah kita dengar, mungkin itu adalah desir angin yang menembus rimbun pepohonan. Tapi hari ini, desir itu makin lirih—bahkan di banyak tempat sudah berubah menjadi gema gergaji mesin. Deforestasi bukan lagi sekadar isu aktivis atau materi seminar lingkungan; ia sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Banjir tahunan, kekeringan yang makin panjang, tanah longsor, hingga harga pangan yang naik-turun seperti grafik saham—semuanya punya akar yang sama: hutan yang menyusut.
Di sinilah satu konsep penting perlu kita angkat lebih tinggi: ekoliterasi. Istilah yang dipopulerkan Fritjof Capra ini merujuk pada kemampuan memahami pola, prinsip, dan hubungan yang menopang kehidupan. Ekoliterasi adalah “melek ekologi”—bukan sebatas tahu nama pohon, tapi paham bagaimana semuanya saling terhubung, dan bagaimana keputusan manusia bisa mengubah nasib satu ekosistem sekaligus.
Hutan dan Universitas Kehidupan
Bayangkan hutan sebagai universitas besar tanpa gedung beton. Pohon-pohon adalah profesor, sungai adalah laboratorium, dan burung serta mamalia adalah peneliti yang bekerja siang-malam menjaga keseimbangan ekosistem. Ketika deforestasi terjadi, kondisinya mirip universitas kehilangan para ilmuwan terbaiknya: kacau, sunyi, dan sistemnya pelan-pelan runtuh.
Contoh paling dekat adalah apa yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro beberapa tahun terakhir. Kawasan hutan di Gondang dan Temayang yang dulu rimbun kini menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ketika tutupan hutan berkurang, tanah kehilangan spons alaminya. Maka tak heran, banjir bandang beberapa waktu lalu menerjang desa-desa di dua kecamatan itu. Air hujan yang deras tak lagi bisa ditahan akar pepohonan; ia meluncur liar membawa tanah, kayu, dan batu. Warga kaget, tapi alam sebenarnya hanya merespons sesuai hukum dasarnya: jika hulu rusak, hilir menanggung akibat.
Kejadian serupa meluas di banyak wilayah Indonesia. Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh baru-baru ini juga mengalami banjir bandang dan longsor besar. Di Sumut, banjir menerjang kawasan permukiman setelah hujan ekstrem mempercepat aliran air dari bukit-bukit yang semakin gundul. Di Sumbar, aliran lahar hujan dari Marapi bercampur dengan kayu-kayu gelondongan yang seharusnya tidak ada di aliran sungai—indikasi deforestasi yang mengabaikan sistem alam. Sementara di Aceh, banjir bandang di beberapa kabupaten terjadi bersamaan dengan longsor di daerah perbukitan, memperlihatkan bahwa vegetasi penahan tanah sudah tidak lagi cukup.
Di semua kasus itu, pola yang sama muncul: deforestasi memperlemah daya lenting ekosistem, dan ketika curah hujan ekstrem datang, bencana menjadi tak terhindarkan.
Ketika Alam Kehilangan Guru, Manusia Kehilangan Arah
Masalah deforestasi akhirnya bukan hanya persoalan hilangnya pohon, tapi hilangnya pengetahuan ekologis yang seharusnya menjadi panduan kita. Tanpa ekoliterasi, manusia mudah tergoda memperlakukan alam sebagai objek ekonomi semata. Kita sering lupa bahwa hujan, air, dan udara bukan hasil pabrik, tetapi hasil harmoninya ekosistem.
Ambil contoh dari Gondang dan Temayang tadi. Banyak warga masih terkejut: “Kok bisa banjir sebesar ini?” Padahal, ketika hutan di perbukitan ditebang secara ilegal atau dikonversi untuk pertanian tanpa kontrol, sistem airnya berubah total. Banjir itu bukan murni bencana alam; ia adalah bencana ekologis yang dipicu keputusan manusia.
Anak-anak perlu belajar bahwa satu pohon bisa menyimpan ratusan liter air. Bahwa akar-akar pohon bekerja seperti anyaman raksasa yang menahan tanah agar tidak longsor. Generasi yang paham hubungan ekologis seperti ini akan tumbuh menjadi masyarakat yang lebih bijak dan pembuat kebijakan yang lebih visioner.
Ekoliterasi dan Kearifan Lokal yang Terlupa
Bangsa kita sebenarnya tidak pernah miskin kearifan ekologis. Masyarakat adat Baduy, Dayak, dan Kajang misalnya, sudah lebih dahulu mengajarkan prinsip ekoliterasi melalui aturan hutan larangan, pola tanam berputar, dan penghormatan pada sumber air. Namun modernisasi sering datang seperti buldoser: cepat, kuat, dan jarang menoleh ke belakang.
Jika kita membaca literatur seperti Deep Ecology karya Arne Naess atau kajian antropologi lingkungan dari Vandana Shiva, kita akan menemukan bahwa masyarakat tradisional sangat “lulusan terbaik” dalam pendidikan ekologi. Mereka tahu bahwa merusak hutan sama saja merusak masa depan.
Dari Eksploitasi ke Regenerasi
Untuk keluar dari lingkaran deforestasi-banjir-longor, kita perlu perubahan paradigma: dari eksploitasi menjadi regenerasi. Carol Sanford dalam The Regenerative Business menekankan bahwa bisnis dan pembangunan tidak cukup hanya “tidak merusak”, tetapi harus mengembalikan fungsi ekologis.
Di Bojonegoro, misalnya, konsep agroforestry bisa menjadi solusi. Menanam kembali pohon keras di area yang rawan banjir bandang, sambil menanam tanaman produktif seperti kopi, porang, atau empon-empon, memberi dua manfaat: ekologis dan ekonomi. Di Sumut, Sumbar, dan Aceh, pendekatan serupa juga bisa diterapkan, ditambah zonasi kawasan rawan bencana yang tegas.
Ekoliterasi sebagai Gerakan Sosial
Ekoliterasi harus menjadi gerakan, bukan hanya kurikulum. Ada beberapa langkah konkret:
1. Sekolah Alam dan Kurikulum Lapangan: Anak-anak perlu melihat akar, menyentuh tanah, dan memahami sungai secara langsung.
2. Kesadaran Jejak Karbon: Warga diajak menghitung jejak ekologisnya sebagaimana mereka menghitung pengeluaran bulanan.
3. Gerakan Reforestasi Berbasis Komunitas: Desa membangun hutan rakyat, kampung hijau, dan patroli antitebang liar.
4. Literasi Media Lingkungan: Film dokumenter, buku, dan konten kreatif menjadi jembatan antara pengetahuan dan aksi.
Pada akhirnya, deforestasi adalah cerita tentang hubungan manusia dan alam yang terganggu. Ekoliterasi adalah cara memperbaiki hubungan itu. Hutan tidak akan bicara, tetapi ia selalu memberi tanda. Ketika banjir bandang di Gondang dan Temayang terjadi, ketika Sumut-Sumbar-Aceh kebanjiran, itu adalah undangan untuk berdialog dengan alam.
Jika kita belajar mendengar, memahami, dan bertindak, masih ada harapan bahwa desir angin di sela pepohonan akan tetap menjadi musik kehidupan. Karena menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan alam—tetapi menyelamatkan diri kita sendiri.
*Ketua PAC Ansor Balen, Pengurus Pusat IKAMI Attanwir Talun







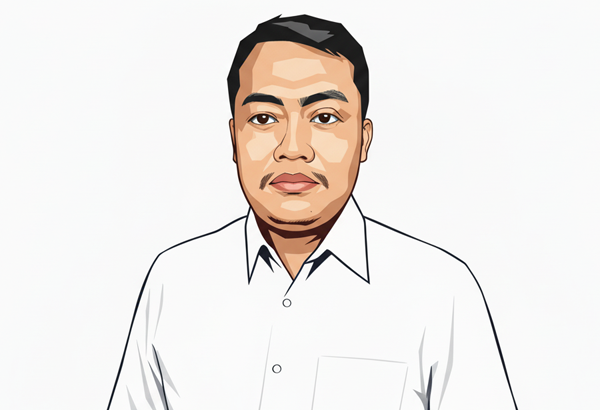









0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published