
Oleh: Choirul Anam*
blokBojonegoro.com - Kalau ada satu tokoh klasik yang pandangannya tetap terasa segar di tengah hiruk-pikuk pendidikan zaman sekarang, Imam Al-Ghazali boleh dibilang salah satunya. Bayangkan saja: hidup hampir seribu tahun lalu, tetapi pemikirannya tentang pendidikan terasa seperti nasihat bijak yang baru keluar dari seminar parenting edisi hari ini. Ia tidak sekadar bicara soal “cara mengajar,” tetapi juga “cara menjadi manusia seutuhnya”—yang akalnya terang, hatinya jernih, dan perilakunya selaras.
Inilah yang hari ini sering kita sebut sebagai pendidikan holistik. Konsep yang menekankan pembentukan manusia secara menyeluruh: intelektual, emosional, moral, spiritual, hingga sosial. Menariknya, jauh sebelum istilah “holistik” keren dipakai dalam kurikulum modern, Al-Ghazali sudah merumuskannya dalam karya-karya besarnya seperti Ihya’ Ulumuddin, Ayyuha al-Walad, hingga Mizan al-‘Amal.
Belajar Bukan Sekadar Menghafal, Tapi Menghidupkan Ilmu
Dalam salah satu nasihatnya kepada murid-muridnya, Al-Ghazali menekankan bahwa ilmu harus diamalkan. “Ilmu tanpa amal itu gila, dan amal tanpa ilmu itu sia-sia,” begitu kira-kira pesan ringkasnya.
Di sinilah letak holistiknya: pendidikan bukan cuma urusan kognitif. Ia menyentuh moral, spiritual, dan aspek kebermanfaatan. Kita mungkin sering bertemu orang yang gelarnya segudang, tetapi sikap dan tindakannya membuat orang kapok berteman. Al-Ghazali pasti akan menggelengkan kepala melihat fenomena itu.
Dalam pendekatannya, ilmu itu hidup ketika ia memperbaiki karakter, bukan hanya menambah hafalan. Ini sejalan dengan gagasan pendidikan karakter modern yang menempatkan nilai, moral, dan empati sebagai pilar penting proses belajar.
Guru Adalah Teladan, Bukan Sekadar Pengajar
Kalau hari ini kita sering bilang "guru adalah role model," Al-Ghazali sudah sejak dulu menyampaikan hal serupa. Ia menulis bahwa guru harus bersikap sebagai orangtua spiritual, bukan hanya penyampai materi pelajaran. Guru tidak cukup hanya “tahu,” tetapi harus “menjadi.”
Dalam Ihya’, ia menggambarkan beberapa etika guru; mengajar dengan kasih sayang, membimbing sesuai kapasitas murid, tidak menjadikan ilmu sebagai alat kesombongan, dan yang paling penting memberi contoh lewat tindakan.
Bayangkan sekolah yang seluruh gurunya menjalankan prinsip ini. Kurang apa coba? Murid tidak hanya pintar, tetapi juga belajar menjadi manusia yang baik dari teladan hidup sehari-hari.
Pendidikan Harus Menyentuh Hati
Salah satu ciri khas pemikiran Al-Ghazali adalah kedalaman spiritualnya. Ia percaya bahwa pendidikan sejati tidak bisa hanya mengandalkan akal; ia juga harus melatih hati (qalb). Dalam kerangka psikologi modern, ini mirip dengan apa yang disebut emotional intelligence atau kecerdasan emosional.
Al-Ghazali mendorong pendidikan agar mampu; menumbuhkan sifat rendah hati, melatih kesabaran, mempertajam empati, menjernihkan niat,dan memperkuat keteguhan moral.
Kalau kita amati, kompetensi-kompetensi ini justru semakin dibutuhkan di era sekarang, ketika informasi begitu mudah diakses tetapi kebijaksanaan terasa langka.
Setiap Anak Unik, Pendidikan Harus Menyesuaikan
Dalam pandangannya, guru harus memahami kemampuan, tabiat, dan kesiapan murid. Tidak ada satu metode yang cocok untuk semua. Al-Ghazali bahkan menyebut bahwa memaksakan beban yang tidak sesuai dengan kemampuan anak adalah bentuk kezaliman.
Konsep ini bersentuhan langsung dengan gagasan modern seperti differentiated learning, pendidikan berbasis minat, dan pendekatan konstruktivistik. Bayangkan kalau sekolah kita secara serius menjalankan prinsip ini, betapa banyak anak yang akan tumbuh tanpa rasa “tertekan” oleh standar yang tidak sesuai dengan dirinya.
Pendidikan Sosial dan Akhlak Sebagai Pondasi
Dalam kurikulum Al-Ghazali, akhlak bukan “sisipan,” tetapi inti dari pendidikan. Tujuan belajar akhirnya adalah membangun manusia yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia menambahkan bahwa seseorang belum bisa disebut berilmu bila ilmunya tidak memperbaiki hubungan sosialnya.
Ini sejalan dengan konsep civic education, pendidikan karakter, dan gagasan modern tentang kompetensi sosial—bagaimana seseorang memahami perannya dalam komunitas, bekerja sama, dan berkontribusi untuk kebaikan umum.
Mengapa Pendidikan Holistik ala Al-Ghazali Relevan Hari Ini?
Kita hidup dalam era yang serba cepat, kompetitif, dan sering kali penuh tuntutan. Anak-anak dikejar nilai, rangking, dan prestasi akademik. Akibatnya, tidak sedikit yang tumbuh jenuh, stres, bahkan kehilangan arah.
Di sinilah warisan Al-Ghazali terasa seperti oase. Ia mengajak kita kembali ke hakekat pendidikan: membentuk manusia seutuhnya. Ia mengingatkan bahwa kepintaran tanpa karakter itu berbahaya. Bahwa guru bukan robot penyampai materi, melainkan pembimbing jiwa. Bahwa hati harus dilatih, bukan diabaikan. Bahwa pendidikan harus sesuai dengan fitrah anak, bukan dipaksa mengikuti standar yang kaku. Dan bahwa tujuan belajar adalah kebermanfaatan, bukan kebanggaan.
Dalam bahasa yang lebih santai, Al-Ghazali seperti berkata: “Jangan bikin sekolah jadi pabrik nilai. Jadikan ia taman yang menumbuhkan manusia.”
Pendidikan holistik ala Imam Al-Ghazali bukan konsep kuno yang usang. Justru, ia menawarkan jalan pulang bagi pendidikan kita yang sering tersesat oleh ambisi angka dan prestise.
Ia mengajak kita untuk melihat anak sebagai manusia yang punya akal, hati, spiritualitas, dan potensi sosial. Ia menempatkan guru sebagai teladan yang menumbuhkan kasih, bukan sebagai operator kurikulum. Ia menegaskan bahwa ilmu harus membentuk laku hidup, bukan hanya memenuhi lembar ujian.
Mungkin inilah saatnya kita kembali mencicipi kebijaksanaan Al-Ghazali: bahwa pendidikan sejati bukan hanya membuat anak berhasil, tetapi juga membuat anak baik, berakal, dan berhati cerah—sebuah kombinasi yang tak lekang oleh zaman. [mad]
*Ketua PAC Ansor Balen









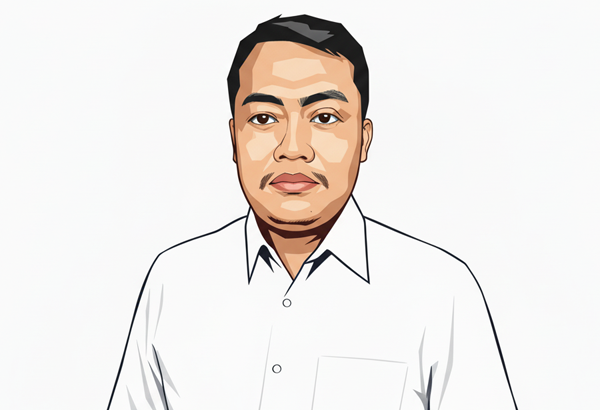







0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published