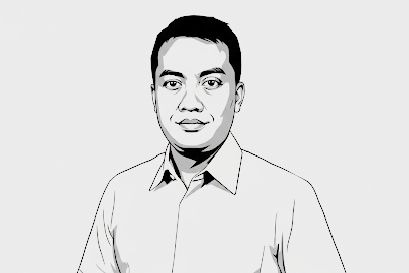
Oleh: Choirul Anam*
blokBojonegoro.com - Pagi itu ponsel remaja bergetar: notifikasi dari Instagram — “Akun Anda tidak lagi tersedia karena Anda berusia di bawah 16 tahun.” Bagi sebagian orang itu menimbulkan panik: foto, chat, kenangan — menguap sementara. Bagi pembuat kebijakan, itu adalah konsekuensi dari sebuah keputusan besar: menempatkan batas usia 16 tahun sebagai ambang aman untuk memiliki akun di platform media sosial besar. Di dunia nyata, kebijakan seperti ini tidak lahir begitu saja—ia muncul dari perdebatan panjang tentang perkembangan anak, kesehatan mental, privasi, dan tanggung jawab perusahaan teknologi.
Baru-baru ini Australia memecah kebekuan global. Pemerintah Canberra mengesahkan amandemen yang memaksa sejumlah platform “berisiko tinggi” untuk mencegah pembuatan dan mempertahankan akun bagi pengguna di bawah 16 tahun — aturan yang mulai diberlakukan pada 10 Desember 2025. Akibatnya, perusahaan seperti Meta sudah mulai menonaktifkan akun yang diperkirakan milik anak 13–15 tahun beberapa hari sebelum tanggal tersebut, memberi contoh nyata bagaimana undang-undang dapat langsung mengubah pengalaman digital anak-anak. Keputusan ini menempatkan Australia di garis depan eksperimen regulasi digital yang tegas.
Mengapa 16 tahun? Angka itu bukan semata-mata angka magis — ia merefleksikan kompromi antara kepentingan perlindungan anak dan pengakuan akan hak berekspresi dan akses informasi. Riset kesehatan mental dan perkembangan menunjukkan bahwa paparan algoritme yang mendesain konten untuk mempertahankan perhatian remaja bisa memperburuk perasaan cemas, citra tubuh, dan gangguan tidur—faktor yang mendorong pembuat kebijakan mengambil langkah-langkah protektif. Namun langkah proteksi selalu menghadapi kritik: apakah pembatasan usia akan mendorong anak-anak ke ruang online yang lebih gelap, atau justru memberi mereka perlindungan yang jelas dan mekanisme hukum untuk menuntut perusahaan? Perdebatan ini masih hidup di ruang akademik dan publik.
Kebijakan Australia memicu gelombang reaksi regional. Malaysia mengumumkan rencana serupa: pemerintah Kuala Lumpur menyatakan niat untuk menaikkan batas usia minimum pembuatan akun sosial media menjadi 16 tahun mulai 2026, sebagai tanggapan terhadap kasus-kasus keamanan dan moral yang melibatkan anak sekolah dan kekhawatiran soal eksploitasi daring. Pernyataan ini menandakan adanya rencana harmonisasi kebijakan di kawasan Asia Tenggara—setidaknya dari sudut pandang regulasi yang lebih protektif.
Selandia Baru juga sedang bergerak ke arah itu. Inisiatif legislatif dan dukungan politik untuk menaikkan usia minimal akses media sosial muncul lewat rancangan undang-undang dan pernyataan pejabat publik selama 2025—menunjukkan bahwa ide “online seperti dunia nyata: ada batas usia” mendapat tempat juga di Negeri Kiwi. Meski mekanik hukumnya berbeda (misalnya ukuran denda dan mekanisme penegakan), roh kebijakan sama: memaksa platform melakukan verifikasi umur dan menanggung tanggung jawab lebih besar atas keselamatan pengguna muda.
Lalu Indonesia? Di sini ceritanya sedikit berbeda: bukan soal ketiadaan perhatian—melainkan soal proses. Sejak 2024–2025, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Kemenko PMK telah aktif membahas regulasi pembatasan usia pembuatan akun media sosial untuk anak. Pemerintah menegaskan tujuan bukan untuk “mengurung” hak anak atas informasi, melainkan menata pembuatan akun: misalnya, memperkuat verifikasi usia, memberi opsi pendampingan orang tua, serta mengatur klasifikasi layanan yang boleh diakses anak. Namun hingga akhir 2025 belum ada tanggal pasti “penerapan nasional” seperti di Australia — proses hukum dan teknis masih terus dirumuskan. Artinya: Indonesia sedang dalam fase perencanaan dan harmonisasi kebijakan, berusaha menyeimbangkan perlindungan anak dengan hak dasar dan konteks sosial budaya lokal.
Bagaimana menilai langkah-langkah ini? Dari sisi edukatif dan argumentatif, ada beberapa poin penting:
1. Perlindungan vs. akses: Batas usia 16 memberi ruang perlindungan; namun harus disertai program literasi digital dan pendampingan keluarga agar anak belajar bertanggung jawab, bukan sekadar “dilarang”.
2. Teknologi verifikasi usia bermasalah: Metode seperti pemeriksaan identitas atau estimasi usia wajah menimbulkan masalah privasi dan akurasi—harus ada standar yang ketat agar tidak menggusur hak privasi anak.
3. Risiko migrasi digital: Pembatasan keras pada platform utama dapat mendorong anak ke platform yang kurang diatur; oleh karena itu perlu kerjasama internasional dan penguatan ekosistem layanan anak-friendly.
4. Peran perusahaan: Platform harus menyediakan opsi transisi (arsip, parental control, edukasi) sehingga ketika akun dinonaktifkan, kepentingan anak dan data mereka tetap terlindungi.
Penutupnya, kebijakan penghapusan atau pembatasan akun anak di bawah 16 oleh Meta di Australia adalah cermin perubahan paradigma: negara kini menuntut akuntabilitas teknologi terhadap generasi muda. Malaysia dan Selandia Baru mengikuti jejak itu, sementara Indonesia tengah meracik resep lokal—antara proteksi, pendidikan, dan penghormatan terhadap hak asasi. Ke depan, yang paling penting bukan hanya “kapan” pembatasan diberlakukan, melainkan bagaimana negara, keluarga, dan platform bersama-sama menyiapkan anak-anak agar tidak sekadar terlindungi dari bahaya, tetapi juga diberdayakan menjadi pengguna digital yang cerdas dan berdaya.
*Ketua PAC Ansor Balen










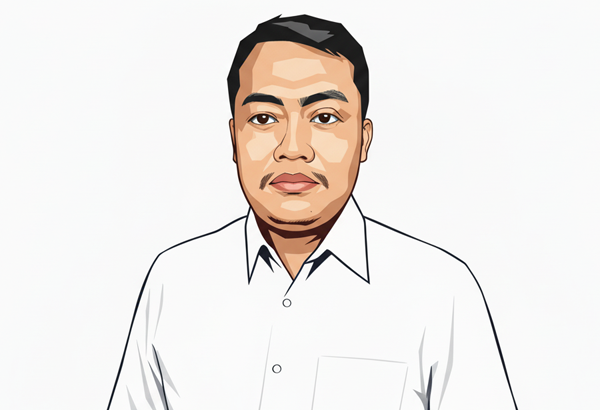






0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published