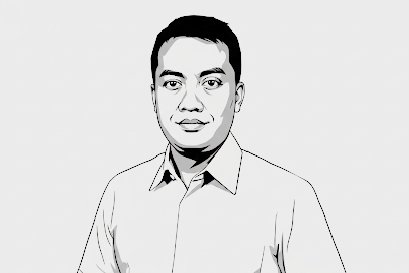
Oleh: Choirul Anam*
blokBojonegoro.com - Siang itu, beberapa hari menjelang Ramadan, kampung saya mulai ramai bukan karena pasar murah atau baliho diskon sirup, tetapi karena aroma apem, kolak, dan nasi berkat yang mengepul dari dapur-dapur. Ibu-ibu sibuk menata tampah, bapak-bapak menenteng rantang, anak-anak mondar-mandir sambil mencicipi “jatah bocoran.” Di kalender, hari itu belum puasa. Tetapi di rasa, kami sudah sedang mempersiapkan diri. Orang Jawa menyebutnya ruwahan atau megengan—sebuah tradisi menyambut Ramadan dengan doa, berbagi, dan menata batin.
Ruwahan berasal dari kata ruh, bulan Syakban dalam penanggalan Hijriah yang oleh orang Jawa disebut bulan “Ruwah.” Di sinilah doa untuk arwah para leluhur dipanjatkan, kuburan dibersihkan, dan ingatan kolektif tentang asal-usul kembali disambungkan. Sementara megengan berasal dari kata megeng (menahan). Menahan diri sebelum benar-benar menahan diri. Ada jeda simbolik: kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, lalu bersiap memasuki Ramadan dengan kesadaran.
Di banyak kampung, ruwahan dan megengan tak pernah kering dari tahlil, yasinan, dan sedekah makanan. Apem menjadi ikon: bulat, lembut, manis. Konon, apem dipautkan dengan kata Arab afwun (maaf), pesan kultural bahwa menyambut Ramadan adalah soal saling memaafkan. Ada kolak pisang dan ketan, nasi berkat, juga bubur merah putih. Setiap makanan bukan sekadar kenyang, tetapi simbol. Di situ Islam tidak hadir sebagai doktrin dingin, melainkan sebagai rasa—yang bisa disantap bersama.
Dari sudut pandang Islam, inti ruwahan dan megengan jelas: doa, silaturahmi, dan sedekah. Nabi Muhammad SAW menekankan keutamaan Syakban sebagai bulan persiapan, bulan di mana amal diangkat (HR. an-Nasa’i). Ulama Nusantara mengartikulasikannya dengan bahasa lokal: bersih kubur, tahlil, berbagi makanan. Ini bukan “tambahan” yang mengaburkan ajaran, melainkan jembatan agar nilai Islam mengakar dalam tanah budaya. Clifford Geertz dalam The Religion of Java mencatat bagaimana Islam Jawa bergerak melalui ritus-ritus sosial yang mempertautkan iman dengan kehidupan sehari-hari. Tradisi tidak menenggelamkan agama; justru membuatnya tinggal di rumah-rumah orang.
Namun, ruwahan dan megengan juga sering disalahpahami. Ada yang menganggapnya bid’ah, ada yang memandangnya sekadar seremoni tanpa makna. Di sinilah pentingnya membaca tradisi sebagai teks sosial. Tradisi bukan kitab suci, tetapi tafsir kolektif atas nilai. Ia boleh berubah, diperdebatkan, dan disesuaikan. Yang tak boleh hilang adalah ruhnya: mempersiapkan diri secara spiritual dan sosial. Jika megengan tinggal acara makan-makan tanpa doa dan refleksi, ia kehilangan makna. Jika ruwahan jadi ajang pamer hidangan, ia kehilangan akhlak.
Di tengah modernitas, ruwahan dan megengan juga diuji. Urbanisasi membuat warga jarang pulang kampung. Grup WhatsApp menggantikan pertemuan di langgar. Kirim “berkat” via kurir lebih praktis daripada datang sendiri. Ada efisiensi, tetapi juga ada kehilangan. Kita kehilangan tatap muka, jabat tangan, dan momen memaafkan yang tak tergantikan emoji. Robert Putnam dalam Bowling Alone mengingatkan tentang merosotnya modal sosial ketika orang makin individualistis. Ruwahan dan megengan, dalam konteks ini, adalah vaksin kultural: ia memaksa kita berkumpul, duduk bersama, dan mengingat bahwa iman juga berwajah sosial.
Secara teologis, doa untuk orang tua dan leluhur sejalan dengan perintah berbakti (birrul walidain). Al-Qur’an mengajarkan doa: “Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira” (QS. al-Isra’: 24). Tradisi ruwahan menerjemahkan ayat itu menjadi praktik: ziarah, tahlil, dan sedekah atas nama mereka. Dalam fiqh, pahala sedekah yang dihadiahkan kepada mayit adalah pendapat yang diterima luas di kalangan ulama. Jadi, ketika orang kampung membawa berkat dan membaca doa, ia sedang mengikat teologi dengan empati.
Secara sosiologis, ruwahan dan megengan merawat egalitarianisme. Di tampah yang sama, si kaya dan si miskin duduk setara. Berkat dibagi tanpa label. Pierre Bourdieu menyebut praktik semacam ini sebagai produksi “modal simbolik”: kehormatan yang lahir dari berbagi. Orang dihormati bukan karena mobilnya, tetapi karena kemurahan hatinya. Tradisi menata hierarki secara halus—menggeser ukuran kemuliaan dari kepemilikan ke kepedulian.
Ada pula dimensi ekologis yang sering luput. Bersih kubur dan kerja bakti menjelang ruwahan mengajarkan kepedulian pada ruang bersama. Kuburan bukan tempat angker yang dihindari, melainkan ruang memori yang dirawat. Kita belajar bahwa merawat yang mati adalah bagian dari merawat yang hidup. Di sana, Islam bertemu dengan kearifan lokal: kebersihan sebagai iman, lingkungan sebagai amanah.
Lalu, apa relevansi ruwahan dan megengan hari ini? Ia relevan justru karena kita lelah oleh percepatan. Tradisi ini memberi rem. Ia memanggil kita untuk “megeng”—menahan diri dari bising dunia, memaafkan sebelum menuntut, berbagi sebelum menimbun. Di tengah algoritma yang memecah, ruwahan dan megengan menyatukan. Di tengah polarisasi, ia mengundang kita duduk satu tikar.
Tentu, tradisi harus terus dikritisi agar tidak membeku. Inklusivitas perlu dijaga: jangan sampai ruwahan hanya milik yang “satu warna.” Ia harus ramah pada yang berbeda, terbuka pada generasi muda, dan adaptif pada konteks kota. Mungkin bentuknya berubah—dari tampah ke kotak nasi—tetapi substansinya jangan hilang: doa, maaf, dan sedekah.
Pada akhirnya, ruwahan dan megengan adalah kisah tentang bagaimana Islam di Jawa tidak datang sebagai palu, melainkan sebagai pelukan. Ia menata batin melalui budaya. Ia mengajarkan bahwa menyambut Ramadan bukan cuma soal kalender, tetapi soal kesiapan jiwa. Dan di setiap apem yang dibagi, ada pesan yang lembut namun tegas: sebelum menahan lapar, tahanlah ego; sebelum memperbanyak ibadah, perbanyaklah maaf.
*Ketua Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) PC Ansor Bojonegoro










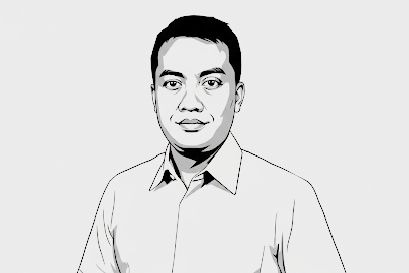






0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published