
Oleh: Choirul Anam*
blokBojonegoro.com - Pernahkah Anda merasa risih saat di minimarket ada orang yang dengan enteng menyerobot antrean? Atau kesal ketika di jalan ada pengendara yang dengan gagah berani melawan arus, seakan-akan lalu lintas dibuat untuk dirinya seorang? Fenomena ini, meski tampak sederhana, seringkali mencerminkan kualitas budaya kita. Budaya antre adalah satu indikator kecil, tapi jelas, bagaimana masyarakat menghargai aturan dan orang lain.
Di sekitar kita, antre sering dianggap sekadar formalitas. Kalau bisa lebih cepat, ya “potong jalur” saja. Bandingkan dengan negara maju seperti Jepang. Di stasiun Tokyo pada jam sibuk, ribuan orang berbaris rapi menunggu kereta. Tak ada yang mendorong-dorong, apalagi menyerobot. Padahal jumlah orangnya jelas lebih banyak dari antrean di warung bakso dekat rumah kita. Mengapa bisa begitu? Karena bagi mereka, antre bukan sekadar menunggu giliran, melainkan ekspresi dari disiplin sosial.
Antre sebagai Pelajaran Sosial
Budaya antre adalah sekolah paling sederhana bagi warga negara. Di sana kita belajar tentang keadilan (siapa datang duluan, dilayani duluan), kesabaran (menunggu gilirannya tanpa protes), serta respek (menghargai hak orang lain). Ini sejalan dengan teori Emile Durkheim tentang “fakta sosial”: kebiasaan kolektif yang membentuk keteraturan masyarakat. Jika antre saja tidak bisa, bagaimana dengan urusan lebih besar seperti pajak, pemilu, atau hukum?
Sayangnya, kita seringkali menganggap antre sebagai beban, bukan latihan moral. Ironinya, orang yang sama yang suka menyerobot antre biasanya juga mengeluh soal “Indonesia kapan maju.” Padahal, maju itu dimulai dari hal-hal remeh seperti ini. Sebenarnya, antre bukan cuma soal berdiri diam menunggu giliran. Ia bisa menjadi ruang literasi kecil yang sering kita abaikan.
Di negara maju, orang memanfaatkan waktu antre untuk membaca koran, novel saku, atau sekadar mencatat ide di ponsel. Kalau kita perhatikan di stasiun kereta Tokyo atau halte bus di London, antrean panjang justru jadi “perpustakaan berjalan.” Orang berdiri rapi sambil sibuk membuka buku atau mengetik catatan.
Di Indonesia, kebiasaan ini mulai terlihat, meski masih jarang. Beberapa anak muda kini memanfaatkan antre di bank, bandara, atau rumah sakit untuk membaca e-book, mengulas buku di Goodreads, atau menulis draft puisi di aplikasi catatan. Sayangnya, mayoritas masih lebih memilih scrolling media sosial tanpa arah, yang seringkali hanya menambah riuh pikiran.
Membaca atau menulis di saat antre adalah latihan ganda: sabar menunggu sekaligus produktif menggunakan waktu. Kalau kebiasaan ini meluas, antre bukan lagi dianggap membosankan, tapi jadi kesempatan belajar. Bayangkan, kalau setiap orang yang antre di loket SIM membawa buku tipis dan bisa selesai membaca satu bab, berapa banyak “jam membaca nasional” yang bisa bertambah tiap hari?
Membaca: Jendela Dunia yang Jarang Dibuka
Beranjak ke budaya membaca. UNESCO pernah merilis data bahwa minat baca masyarakat Indonesia tergolong rendah—hanya sekitar 0,001, artinya dari seribu orang, hanya satu yang punya kebiasaan serius membaca. Sementara di negara-negara maju, membaca adalah aktivitas sehari-hari. Di kereta bawah tanah di Seoul atau London, orang-orang sibuk membuka buku, majalah, atau kini e-book.
Di kita? Kalau naik kereta, kebanyakan sibuk scrolling TikTok atau membuka chat WhatsApp grup arisan RT. Bukan berarti salah, tapi ketika bacaan yang dikonsumsi hanya potongan meme atau berita hoaks, maka kedalaman berpikir kita ikut terpengaruh.
Membaca itu ibarat membuka jendela ke dunia yang lebih luas. Tanpa membaca, kita seperti tinggal di rumah gelap, hanya mengandalkan kabar dari mulut ke mulut. Tak heran, banyak orang gampang terprovokasi isu politik atau agama yang dangkal, karena tidak punya bekal literasi untuk menyaring informasi.
Menulis: Dari Coretan Menjadi Peradaban
Kalau membaca itu jendela, maka menulis adalah pintu kita masuk ke ruang peradaban. Di dunia maju, tradisi menulis begitu kuat. Mahasiswa di Eropa sejak awal kuliah sudah dibiasakan menulis esai kritis. Di Jepang, anak SD sudah membuat jurnal harian yang dievaluasi gurunya.
Bandingkan dengan kita. Menulis sering dianggap momok. Tugas menulis makalah saat kuliah sering diselesaikan dengan copy-paste dari internet. Padahal, menulis melatih otak kita untuk merangkai logika, mengorganisir ide, sekaligus memperjelas apa yang kita pahami.
Budaya menulis rendah biasanya berjalan seiring dengan budaya membaca yang minim. Orang sulit menulis karena bahan bacaan sedikit. Sebaliknya, jika kita rajin membaca, menulis akan mengalir lebih mudah.
Tiga Budaya, Satu Akar
Antre, membaca, dan menulis sebenarnya punya benang merah yang sama: disiplin berpikir dan menghargai orang lain. Antre melatih kita menghargai waktu dan hak orang lain. Membaca melatih kita menghargai pengetahuan orang lain. Menulis melatih kita menghargai pikiran kita sendiri dengan cara yang terstruktur.
Negara maju tampak tertib bukan semata karena hukum yang ketat, tapi karena warganya sudah terbiasa dengan tiga budaya ini. Mereka sadar bahwa antre itu bagian dari keteraturan publik, membaca itu nutrisi otak, dan menulis itu warisan pengetahuan.
Di Indonesia, kita sering berhenti di jargon. Kita bangga dengan istilah “membaca adalah jendela dunia,” tapi perpustakaan sekolah sering lebih mirip gudang buku berdebu. Kita sering mengutip “pena lebih tajam dari pedang,” tapi pena kita jarang digunakan kecuali untuk tanda tangan presensi.
Menghidupkan Kembali Tradisi
Lalu bagaimana menghidupkan budaya ini? Pertama, mulai dari rumah. Orang tua bisa melatih anaknya untuk antre saat membeli jajanan, atau memberi contoh membaca buku di rumah, bukan hanya sibuk menatap layar televisi. Kedua, sekolah. Guru sebaiknya tidak hanya memberi tugas menulis, tetapi juga membimbing prosesnya: dari riset kecil, menyusun kerangka, hingga menulis refleksi. Ketiga, ruang publik. Pemerintah perlu memperbanyak fasilitas literasi—taman bacaan, perpustakaan digital, atau klub menulis di komunitas lokal.
Lebih jauh, kita perlu membangun kebanggaan bahwa antre, membaca, dan menulis itu keren. Bayangkan kalau di media sosial lebih banyak muncul tren “book review” daripada sekadar joget challenge. Atau kalau orang merasa bangga bisa menulis opini di surat kabar lokal daripada hanya berdebat di kolom komentar Facebook.
Seorang filsuf Jerman, Jürgen Habermas, pernah menekankan pentingnya “ruang publik” yang sehat, tempat warga berdialog dengan rasional. Budaya antre, membaca, dan menulis adalah fondasi dari ruang publik itu. Tanpa ketiganya, kita mudah jatuh pada budaya instan: ingin cepat, malas berpikir, dan tidak terbiasa mengekspresikan gagasan.
Jadi, kalau kita ingin Indonesia maju, mari mulai dari antre yang rapi, membaca yang serius, dan menulis yang konsisten. Tiga hal sederhana ini bisa menjadi bahan bakar peradaban. Karena bangsa besar bukan hanya yang tinggi gedungnya atau banyak mobilnya, melainkan yang warga negaranya sabar mengantre, rajin membaca, dan tekun menulis. [mad]
*Ketua PAC GP Ansor Balen, Perangkat Desa Margomulyo, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro
















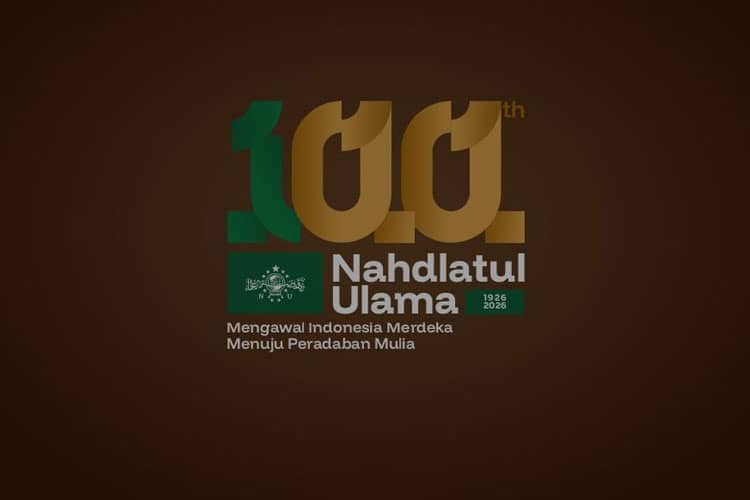
0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published