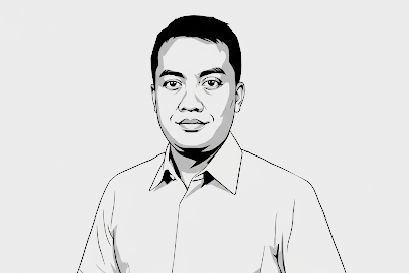
Oleh: Choirul Anam*
blokBojonegoro.com - Ada satu momen dalam hidup beragama yang seharusnya kita jaga betul-betul: saat simbol, ruang, dan suasana sakral sedang bekerja membentuk kesadaran kita. Isra Mikraj bukan sekadar agenda tahunan yang kita lewati sambil lalu. Ia adalah peristiwa spiritual—tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW menembus batas ruang dan waktu, tentang shalat sebagai “oleh-oleh langit”, dan tentang disiplin ruhani yang mestinya meresap sampai ke cara kita bersikap di bumi.
Karena itu, wajar jika publik tersentak ketika muncul kabar tentang aksi biduan di panggung peringatan Isra Mikraj di Banyuwangi. Panitia mengklaim hiburan itu digelar setelah acara resmi rampung. Tetapi di mata publik, yang terlihat bukan soal jam berapa acara dimulai atau selesai, melainkan soal ruang simbolik yang belum “bersih” dari makna sakral. Spanduk, panggung, suasana—semuanya masih memanggil memori tentang Nabi, tentang shalat, tentang adab.
Waketum MUI, Anwar Abbas, menyebut hal itu sebagai sesuatu yang tidak etis dan tidak elok. Bukan karena Islam anti hiburan, tetapi karena ada konteks yang dilanggar. Dalam Islam, tempat dan waktu bisa berubah makna tergantung peristiwa yang melekat padanya. Masjid berbeda dengan pasar. Majelis taklim berbeda dengan panggung dangdut. Ketika batas itu kabur, yang terjadi bukan sekadar “hiburan setelah acara”, tapi benturan simbolik.
Masalahnya bukan soal biduan atau jogetnya semata. Ini soal kepekaan. Soal apakah kita masih mampu membedakan mana ruang untuk tafakur dan mana ruang untuk bersenang-senang. Kita hidup di zaman ketika segala hal ingin dibungkus meriah, viral, ramai. Kadang, dakwah pun tergoda mengikuti logika panggung: yang penting ramai dulu, substansi belakangan. Di sinilah dakwah sering tergelincir—bukan karena niatnya buruk, tetapi karena sensitivitasnya tumpul.
Panitia mengaku hiburan itu inisiatif spontan untuk internal. Mereka juga sudah minta maaf. Itu baik dan patut diapresiasi. Tetapi kegaduhan ini tetap memberi pelajaran penting: bahwa dalam urusan simbol agama, ukuran “niat baik” saja tidak cukup. Ada dimensi etika publik yang harus diperhitungkan. Masyarakat melihat, menilai, dan merasakan. Dan perasaan umat bukan hal sepele.
Bayangkan jika seseorang baru saja larut dalam ceramah tentang Isra Mikraj—tentang shalat lima waktu sebagai tiang agama—lalu dalam hitungan menit, di panggung yang sama, muncul joget dan nyanyian yang auranya jauh dari nilai kesakralan tadi. Yang rusak bukan hanya estetika, tapi juga kontinuitas pesan. Dakwah kehilangan momentumnya.
Kita perlu jujur mengakui: ada kegagapan dalam cara kita mengelola acara keagamaan. Banyak panitia bekerja keras, ikhlas, bahkan sering tanpa bayaran. Tapi kadang kita lupa satu hal penting: acara keagamaan bukan sekadar soal teknis—siapa mengisi, jam berapa, selesai kapan. Ia juga soal rasa, adab, dan pesan simbolik.
Islam tidak melarang hiburan. Nabi pun tidak mematikan kegembiraan. Tapi beliau sangat menjaga konteks. Ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk serius. Ada tempat untuk bersuka, ada tempat untuk tunduk. Ketika semuanya dicampur tanpa sekat, yang terjadi bukan inklusivitas, melainkan banalitas—agama terasa biasa, kehilangan wibawa.
Kasus Banyuwangi ini seharusnya tidak kita lihat sebagai sekadar “kesalahan panitia desa”. Ia cermin dari wajah dakwah kita hari ini. Apakah kita masih memuliakan ruang sakral, atau sudah terlalu terbiasa mengubahnya jadi panggung serba bisa?
Kita sering ingin mendekatkan agama pada masyarakat dengan cara yang “ramah”, “menghibur”, dan “tidak kaku”. Itu niat baik. Tapi jika caranya justru mengaburkan nilai yang hendak dijaga, maka kita perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk merenung.
Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak hiburan di acara keagamaan, melainkan lebih banyak kesadaran. Kesadaran bahwa dakwah bukan soal ramai-ramai, tapi soal dalam-dalam. Bukan soal viral, tapi soal bernilai.
Peringatan Isra Mikraj seharusnya mengantar kita pada disiplin shalat, pada etika hidup, pada adab sosial. Jika panggungnya justru jadi tempat kontroversi, maka ada yang salah dalam manajemen makna.
Kita patut bersyukur panitia sudah minta maaf. Itu menunjukkan tanggung jawab. Tapi yang lebih penting: kita semua—panitia, kiai, tokoh masyarakat, jamaah—perlu belajar ulang soal adab ruang dan waktu. Agar ke depan, tidak ada lagi dakwah yang tersandung oleh hiburan.
Karena dakwah sejatinya bukan tentang seberapa meriah acaranya, tetapi seberapa dalam ia menancap di hati. Dan hati, seperti juga ruang sakral, tidak bisa diperlakukan sembarangan. [mad]
*Ketua PAC Ansor Balen dan Pengurus Pusat IKAMI Attanwir Talun


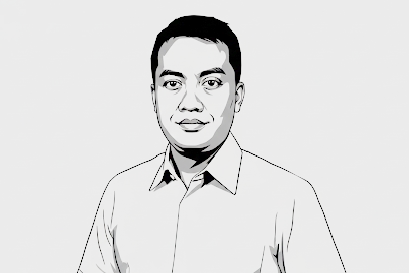
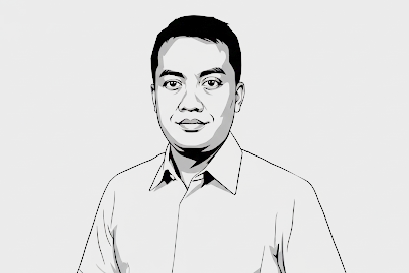
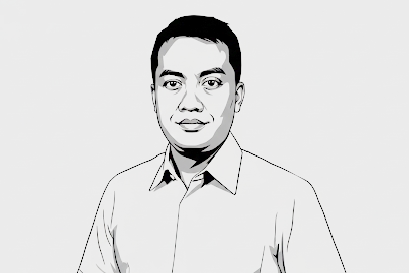

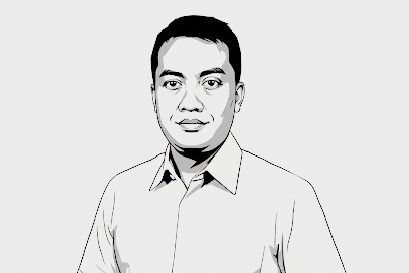
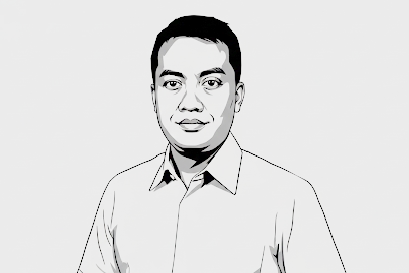
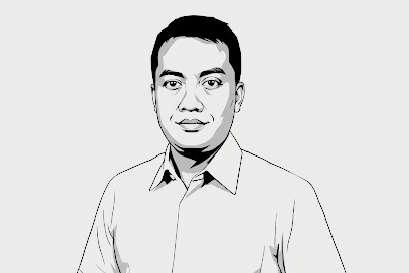


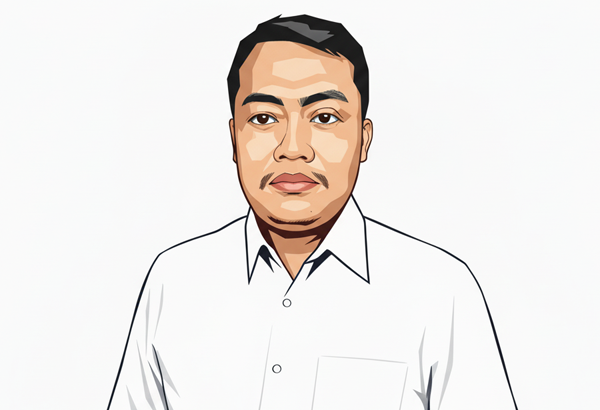





0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published