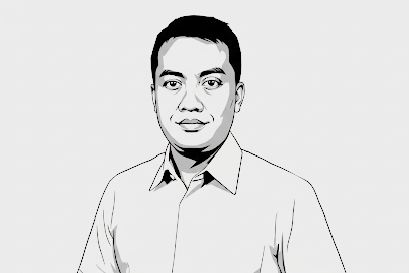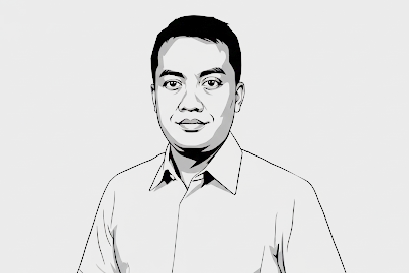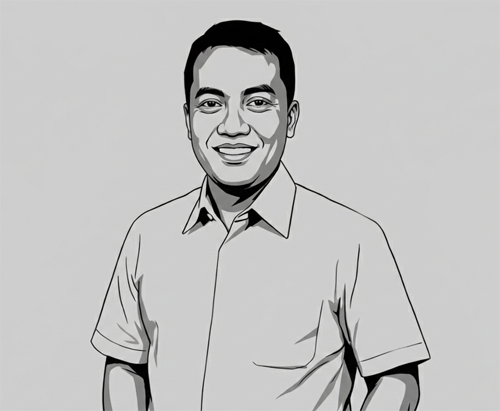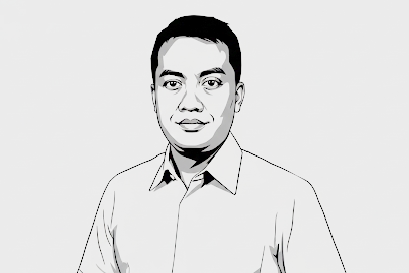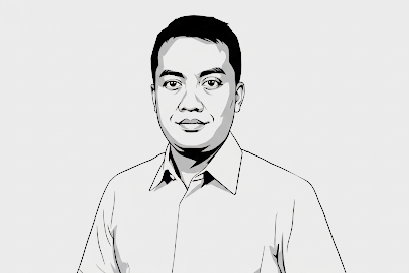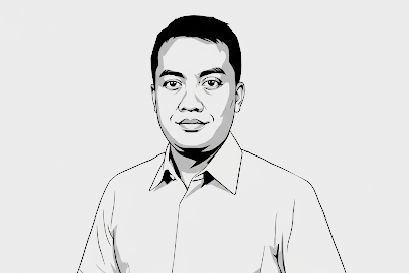Kolom
Seribu Bulan dalam Satu Malam
Ada satu malam dalam setahun yang selalu membuat orang-orang rela mengurangi tidur. Masjid mendadak ramai, mushaf Al-Qur’an dibuka lebih lama dari biasanya, dan doa-doa dipanjatkan dengan suara lirih bercampur harap. Malam itu dikenal sebagai Lailatul Qadar—malam yang oleh Al-Qur’an disebut lebih baik daripada seribu bulan.