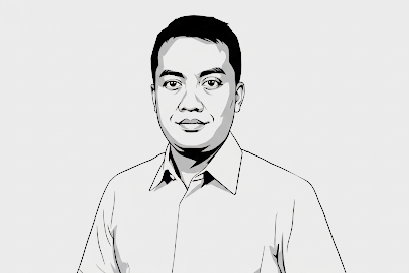
Oleh: Choirul Anam*
blokBojonegoro.com - Pagi itu, saya melihat seorang ibu di sudut desa menyiapkan sarapan. Kompornya sederhana, panci kecil di atas tungku. Ia merebus daun kelor, menggoreng tempe, dan menanak nasi. Anaknya duduk di lantai, memainkan tutup botol sambil sesekali menengok ke dapur. Dari luar, pemandangan itu tampak biasa saja. Tapi sebenarnya, di dapur kecil itulah masa depan seorang anak sedang dimasak.
Masalahnya, tidak semua dapur hari ini menyajikan menu seperti itu.
Di banyak rumah, tempe diganti mi instan. Sayur diganti sosis. Ikan diganti nugget. Cepat, murah, mengenyangkan. Tapi tidak selalu menyehatkan. Dan dari kebiasaan kecil yang berulang setiap hari itulah tengkes—atau stunting—pelan-pelan tumbuh tanpa suara.
Tengkes bukan sekadar soal anak bertubuh pendek. Ia adalah tanda bahwa seorang anak mengalami kekurangan gizi dalam waktu lama, bahkan sejak masih dalam kandungan. Dampaknya tidak main-main: pertumbuhan otak terganggu, daya tahan tubuh lemah, dan di masa depan produktivitasnya bisa menurun. Anak tengkes hari ini adalah generasi rapuh esok hari.
Ironisnya, semua itu terjadi di negeri yang sebenarnya kaya pangan.
Indonesia bukan negara miskin makanan. Kita punya tempe, tahu, telur, ikan laut dan tawar, singkong, jagung, pisang, pepaya, labu, daun kelor, kacang-kacangan. Semua tumbuh di tanah sendiri. Semua relatif murah. Semua bergizi. Tapi justru di tengah kelimpahan itulah banyak anak kekurangan zat gizi penting: protein, zat besi, zinc, vitamin A.
Masalahnya bukan karena tidak ada makanan. Tapi karena yang dimakan tidak seimbang.
Kita sering menyamakan kenyang dengan sehat. Padahal kenyang belum tentu cukup gizi. Anak bisa makan tiga kali sehari, tapi kalau isinya hanya nasi, mi, dan gula, tubuhnya tetap “lapar” nutrisi. Otaknya kekurangan bahan bakar untuk tumbuh. Tubuhnya kekurangan zat untuk membangun sel.
Di sinilah hubungan tengkes dan pangan lokal menjadi sangat dekat.
Pangan lokal sebenarnya adalah kunci pencegahan tengkes. Karena ia: Mudah diakses, Murah, Sesuai budaya, Kaya zat gizi alami
Satu piring sederhana berisi nasi, tempe, telur, ikan, dan sayur lokal sudah memenuhi kebutuhan gizi anak. Tidak perlu mahal. Tidak perlu impor. Tidak perlu ribet.
Tapi di banyak tempat, pangan lokal justru dianggap “makanan kampung”. Kurang keren. Kurang modern. Anak-anak lebih bangga makan nugget dan minum minuman manis kemasan daripada makan ikan dan sayur bening. Dan orangtua sering membiarkan, karena yang penting anak mau makan.
Di situlah tengkes tumbuh diam-diam.
Saya pernah berbincang dengan seorang ibu. Anaknya pendek untuk usianya. Ketika ditanya apa yang sering dimakan anaknya, ia menjawab jujur, “Yang penting kenyang, Mas. Biasanya nasi sama mi. Kadang sosis.”
Ia tidak jahat. Ia tidak lalai. Ia hanya tidak cukup tahu bahwa anaknya butuh lebih dari sekadar kenyang. Anak butuh seimbang.
Karbohidrat saja tidak cukup. Tubuh anak butuh: Protein untuk membangun otak dan otot, Lemak sehat untuk perkembangan sel, Vitamin dan mineral untuk daya tahan tubuh
Semua itu ada di pangan lokal. Tapi tanpa literasi gizi, pangan lokal hanya lewat di pasar tanpa pernah masuk ke piring anak.
Pemerintah sudah melakukan banyak hal. Ada posyandu, edukasi gizi, hingga program Makan Bergizi Gratis. Itu penting. Tapi kita harus jujur: negara hanya bisa membantu sebagian. Sisanya terjadi di rumah.
Karena satu anak makan di sekolah satu kali. Tapi makan di rumah dua sampai tiga kali sehari.
Artinya, perang melawan tengkes tidak dimenangkan di kantor kementerian. Ia dimenangkan di dapur.
Di dapur tempat ibu memilih antara tempe atau sosis.
Di dapur tempat ayah memberi contoh makan sayur atau tidak.
Di dapur tempat anak belajar bahwa makan itu bukan soal rasa saja, tapi juga soal kesehatan.
Pangan lokal bukan hanya soal tradisi. Ia adalah strategi masa depan.
Daun kelor yang sering diremehkan itu, misalnya, kaya zat besi dan vitamin. Ikan kecil di sungai kaya protein. Tempe dari kedelai lokal kaya asam amino. Semua itu adalah senjata melawan tengkes—tanpa harus mahal.
Masalahnya, kita sering mencari solusi jauh, padahal jawabannya dekat.
Tengkes bukan takdir. Ia adalah hasil dari kebiasaan yang bisa diubah.
Ketika sebuah keluarga mulai mengganti satu porsi mi instan dengan tempe dan sayur, itu bukan perubahan kecil. Itu investasi masa depan. Ketika seorang ibu mulai membiasakan anak makan ikan, itu bukan soal selera. Itu soal kecerdasan generasi.
Di Hari Gizi Nasional atau hari apa pun, kita seharusnya tidak hanya bicara tentang angka stunting dan target persentase. Kita perlu bicara tentang isi piring kita sendiri.
Karena di sanalah masa depan bangsa sedang dibentuk—dalam senyap.
Di dapur kecil itu, di meja makan sederhana itu, di tangan seorang ibu yang menanak nasi dan menggoreng tempe.
Dan mungkin, masa depan Indonesia tidak sedang dibangun di gedung tinggi. Ia sedang dimasak perlahan—di panci-panci kecil, oleh orang-orang biasa, yang jika paham gizi, bisa melahirkan generasi luar biasa.
*Ketua Badan Usaha Milik Ansor (BUMA) PC Ansor Bojonegoro



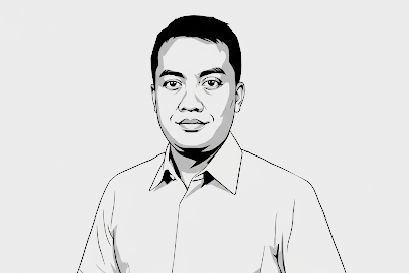
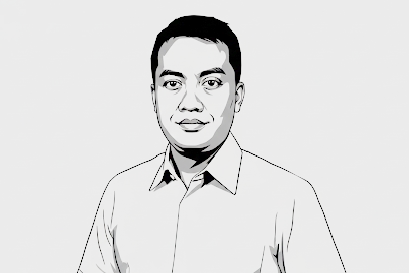
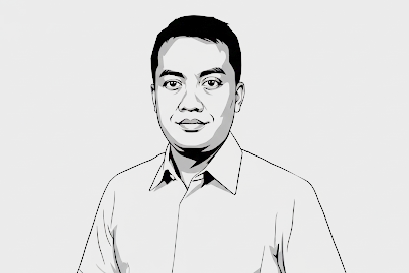
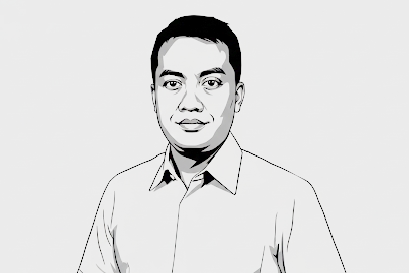

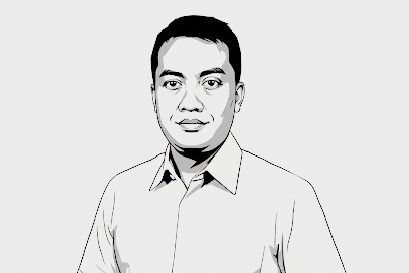
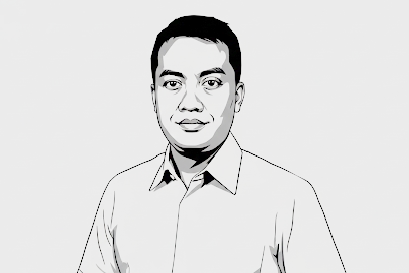
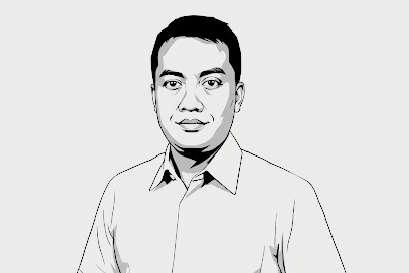





0 Comments
LEAVE A REPLY
Your email address will not be published